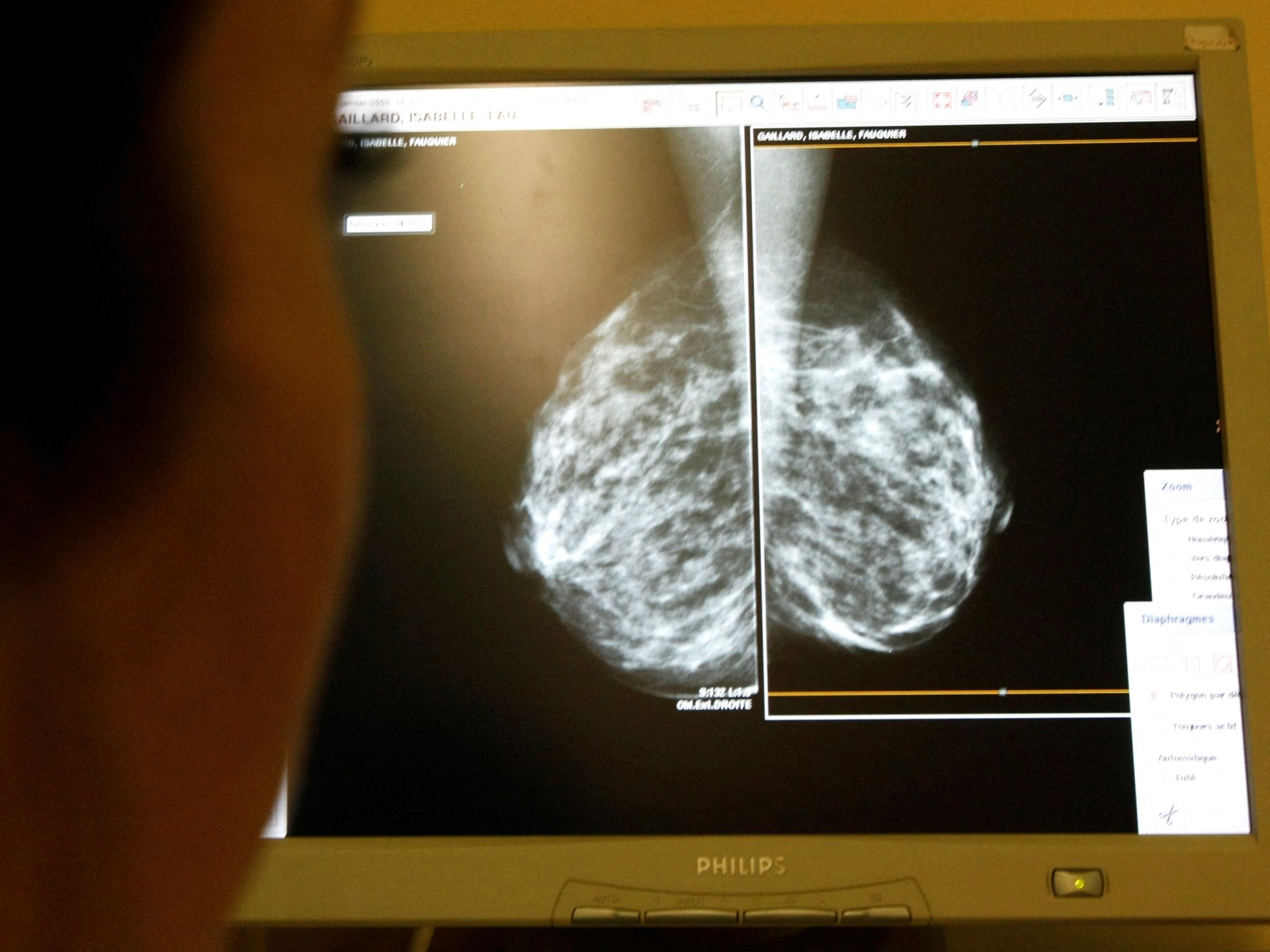Pada 17 Februari, besar demonstrasi mengguncang Paramaribo, ibu kota negara Amerika Selatan dan bekas jajahan Belanda di Suriname. Ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes korupsi pemerintah, inflasi yang tak terkendali, dan keputusan Presiden Chan Santokhi untuk mengakhiri subsidi pemerintah untuk listrik, bahan bakar, dan barang-barang penting lainnya.
Seperti yang bisa diduga, penghapusan subsidi terjadi di bawah bimbingan Dana Moneter Internasional (IMF), yang telah lama berspesialisasi dalam mengatasi krisis ekonomi internasional dengan meningkatkan kesengsaraan anggota masyarakat termiskin.
IMF Suriname saat ini program restrukturisasi pinjaman dan utang hanyalah salah satu dari banyak pencapaian Santokhi yang meragukan, yang setelah menjabat pada tahun 2020 mengangkat istrinya ke berbagai posisi yang menguntungkan, termasuk Dewan Pengawas dari perusahaan minyak negara Staatsolie.
Saya tiba di Paramaribo pada bulan April, dua bulan setelah protes anti-pembatasan pada bulan Februari, dan berbicara dengan Ahilia Welles, seorang aktivis, guru, dan politikus Suriname – dalam urutan itu, dia menyebutkan – yang menghadiri rapat umum tersebut dan dipukuli kakinya dengan air mata. tabung gas yang ditembakkan polisi. Pria di sebelahnya segera mengambil perangkat berbahaya itu, katanya, dan melemparkannya kembali ke pasukan hukum dan ketertiban. “Saat itulah saya tahu orang Suriname benar-benar marah,” katanya kepada saya.
Menurut menulis dari peristiwa hari itu oleh kantor berita Reuters, protes damai “berubah menjadi buruk ketika pengunjuk rasa yang melemparkan batu dan botol ke arah polisi menyerbu halaman parlemen”.
Pada gilirannya, Kedutaan Besar AS di Paramaribo memiliki a penyataan mengutuk “serangan para pengunjuk rasa terhadap gedung Majelis Nasional Suriname dan tindakan kekerasan terkait sebagai serangan yang tidak dapat diterima terhadap demokrasi” – seolah-olah ada sesuatu yang demokratis tentang sebuah negara di mana itu adalah kejahatan untuk menghina presiden dan mengungkapkan penghinaan terhadap pemerintah.
Seperti kekuatan dunia yang dilukisnya, tentu saja, setiap manifestasi keputusasaan publik massal yang mengarah pada penghancuran negara dan kepemilikan pribadi entah bagaimana lebih “keras” daripada, Anda tahu, menghancurkan kehidupan manusia dengan kebijakan ekonomi yang jahat.
Welles memberi tahu saya bahwa dalam pekerjaan mengajarnya saat ini di distrik Para, Suriname utara, sejumlah muridnya sering absen dari kelas karena mereka harus bekerja untuk membantu keluarga mereka bertahan hidup. Siswa lain akan tiba di sekolah tanpa makanan untuk hari itu, situasi yang coba dikompensasi oleh Welles dengan membawa makanan ke kelas.
Sampai, dia tidak mampu lagi melakukannya sendiri.
Inisiatif Santokhi lainnya adalah membatasi gaji guru, sebuah kebijakan yang bertentangan dengan konsensus neoliberal yang tampaknya de facto bahwa mereka yang bertanggung jawab untuk mendidik generasi muda suatu bangsa dan membuka jalan bagi masa depan, seharusnya tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri. .
Pada tanggal 27 April, beberapa hari setelah saya tinggal di Paramaribo, saya kebetulan melihat protes seorang guru di pusat kolonial kota, di mana kemarahan terlihat jelas, tetapi saya hanya memiliki satu kata Belanda – “di bawah air” – dalam pidato yang berapi-api oleh sebuah persatuan. . resmi.
Memang, sebagian besar negara telah terendam air sejak kedatangan saya karena hujan lebat dan banjir, menyebabkan penutupan sekolah, menjebak banyak orang di rumah mereka, dan menyoroti kurangnya perhatian pemerintah untuk mengatasi ancaman eksistensial domestik yang nyata.
Saya datang ke Suriname tanpa agenda khusus, meskipun duduk di dalam ruangan dan menyaksikan intrusi air yang dipenuhi ular melalui jendela diakui bukanlah salah satu pilihan yang dipertimbangkan.
Ketika klaustrofobia menguasai saya, seorang lelaki tua Afro-Suriname bernama Ricky, yang kenalan pra-diluvia yang saya kenal di Paramaribo, menawarkan untuk menjemput saya dengan mobil bobroknya.
Hasil dari upaya murah hati ini adalah air merembes ke pintu kendaraannya saat kami menepi di jalan saya, dan dia berganti-ganti antara memohon dengan putus asa kepada Tuhan dan kata-kata kutukan terhadap pemerintah, cuaca, dan IMF – sebuah entitas. yang menurut Ricky tidak ingin dia bisa membeli bensin, roti atau apapun.
Dia membawa saya ke toko milik orang Cina untuk membeli sepatu hujan anti ular setinggi lutut, dan saya berjalan pulang.
Ketika banjir untuk sementara mereda, Ricky dan saya mengunjungi tempat kelahiran Anton de Kom, ikon antikolonial Suriname dan pejuang perlawanan Perang Dunia II. Dalam karya 1934 tanda tangannya Budak Suriname Kamimenulis de Kom tentang bagaimana, pada pergantian abad ke-17 di Suriname kolonial, “orang kulit putih bebas mengumpulkan kekayaan tanpa perlawanan” sementara budak adalah “milik pribadi dan aset bergerak”—suatu keadaan yang didorong oleh orang Suriname. memunculkan pepatah: “Kecoak tidak bisa menuntut haknya di mulut burung.”
Di seberang bekas kediaman de Kom terdapat grafiti putih dengan latar belakang biru yang mencela “geng” IMF.
Suriname tentu bukan negara pertama atau terakhir yang terjebak oleh sistem keuangan global yang didominasi AS. Kapitalisme sendiri adalah kekuatan yang adiktif. Banjir Suriname terjadi secara metaforis menangkap bagaimana suatu bangsa dapat tenggelam di bawah tirani elit.
Dan meskipun perbudakan, kolonialisme, dan semua fenomena buruk itu seharusnya sudah terjadi di masa lalu, ada kesamaan yang mengganggu dengan masa kini tidak hanya di Suriname, tetapi juga di negara-negara lain di Global Selatan.
Pada 2017, Tunisia juga menandatangani perjanjian pinjaman dengan IMF. Dalam setahun, pergolakan anti-penghematan melanda negara Afrika Utara itu karena rakyat Tunisia menderita akibat “reformasi ekonomi” yang disponsori IMF.
Saat itu saya sedang berbicara dengan profesor di Universitas Tunis Corinna Mullinyang mencatat bahwa periode pasca-kolonial Tunisia kebetulan memiliki “banyak kesinambungan struktural dengan bentuk akumulasi dan perampasan yang menjadi ciri pemerintahan kolonial Prancis”, yang berakhir pada tahun 1956.
Hari-hari ini, kata Mullin, “lembaga keuangan internasional, Uni Eropa, AS dan aktor (neo)kolonial-kapitalis terkemuka lainnya” telah termakan dengan memaksa “‘pembangunan’ neoliberal” ke tenggorokan Tunisia – tetapi hanya “untuk kepentingan internasional.” dan segmen modal lokal”.
Dengan kata lain: pepatah paruh burung.
Meksiko juga mengalami tekanan kapitalisme global, seperti ketika subsidi pertanian secara teoretis diizinkan oleh Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, berkat persyaratan yang dikenakan pada pinjaman IMF dan AS yang diberikan kepada negara tersebut pada 1980-an dan awal 1990-an (NAFTA) tahun 1994 hanya berlaku untuk “mitra” NAFTA Meksiko yang lebih kaya dan lebih kuat, Amerika Serikat dan Kanada.
Sebagai jurnalis Garry Leech dalam babnya tentang buku Suaka untuk dijual: keuntungan dan protes dalam industri migrasi, terutama agribisnis AS, telah mampu mengeksploitasi bias cabul, “kekerasan struktural lebih lanjut yang telah menghancurkan kehidupan jutaan petani Meksiko melalui pembuangan produk makanan AS yang disubsidi secara besar-besaran oleh NAFTA di pasar Meksiko”.
Begitu banyak untuk “perdagangan bebas” – atau kebebasan secara umum.
Di sini, di Suriname, banjir akhirnya surut – namun banyak penduduk masih tenggelam dalam kesulitan.
Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan posisi redaksi Al Jazeera.